
saya begitu tertarik dan terkesan dengan gaya penulisan dari danarto. banyak yang berkata danarto adalah seorang penulis yang bermahzab "realisme magis". selamat menikmati cerpen ini.
Cerpen Danarto
Ketika ibu mendapatkan cincin kawinnya berada di dalam perut ikan yang sedang dimakannya, seketika ibu terkulai di meja makan, pingsan. Lalu koma sekitar satu minggu, kemudian ibu meninggal dunia. Sejak saat itu sejarah hidup keluarga kami diputar ulang. Seperti digelar di kamar keluarga, juga di pekarangan belakang rumah, hari demi hari diperlihatkan malaikat betapa cara kerja langit tak mempunyai patokan. Tak dapat ditebak. Tak terduga. Dalam mengarungi pemandangan yang terbentang di hadapan, kami tak tahu benar apakah itu pemandangan alam atau lukisan pemandangan alam di atas kanvas.
Kami juga sering turun dari kendaraan umum lalu beramai-ramai menambal aspal jalan yang mengelupas. Atau mendorong bus kami yang terjerembab banjir. Pemandangan indah, pemandangan suram, semua disajikan kepada kami.
Kami harus jujur, kami sekeluarga bukan kumpulan orang-orang baik tapi kami mematuhi rambu-rambu lalu-lintas. Hidup kami baik-baik saja sampai gempa yang berkekuatan dahsyat itu jatuh dari angkasa. Seluruh bangunan porak-poranda sampai sekecil-kecilnya rata dengan tanah. Nama, watak, kelakuan, pikiran, emosi, keberuntungan, dan nasib jelek, berputar-putar di dalam kubangan rajah tangan yang sudah dicetak di dalam K.T.P. yang tersimpan dalam segel laminasi dengan warna emas.
Jika kami bongkar, apa satpam tidak marah? Jika tidak kami bongkar, kami megap-megap. Tapi itulah harga mati dari rantai yang sudah telanjur bergandengan.
Hari itu hari yang mendidih. Walau hujan sehari-harinya, Desember yang hitam-pekat oleh bara yang menganga telah membayangi hidup kami sekeluarga setiap detiknya. Hari belum tinggi benar ketika ayah diseret ke tepi Sungai Brantas bersama puluhan orang --laki-laki dan perempuan-- yang duduk dengan mata tertutup dan tangan terikat ke belakang. Mereka basah-kuyup menggigil kedinginan oleh hujan dan kepanasan oleh hantu yang mengintip dari balik kancing baju mereka. Persis gundukan tanah yang tumbuh berderet-deret menghiasi sungai, mereka gundukan-gundukan yang tak dikenal. Gundukan semak belukar yang setiap saat dibabat supaya kelihatan rapi.
Ketika itu mata saya mengintip dari balik semak dalam hujan lebat yang tak mau tahu. Mata yang berumur sekitar dua puluh delapan tahun. Mata yang menatap tajam di antara tetesan hujan deras itu. Saya menyaksikan satu per satu dari leher orang-orang yang duduk termangu-mangu setelah disambar kilatan putih menyemburkan cairan merah dengan deras ke udara. Lalu tubuh-tubuh yang masih duduk tak berkepala itu didorong terjungkal ke sungai. Tubuh-tubuh itu tenggelam lalu tersembul kembali. Dalam sekejap mayat-mayat yang mengapung-apung itu memenuhi seluruh permukaan Sungai Brantas.
Rasanya hujan bertambah deras. Para petugas yang telah melaksanakan perintah itu, dalam keadaan basah-kuyup berlarian dengan pedang yang telanjang berkilatan oleh cahaya petir, menuju sejumlah truk yang telah kosong, lalu tancap gas meninggalkan kawasan itu. Dengan menjerit-jerit memanggili ayah, saya yang menggigil dalam hujan penuh geledek menyambar-nyambar, berlari menyusuri tepi sungai mengikuti mayat-mayat yang mengapung dibawa deras air.
Lalu saya terjun ke sungai berusaha keras mencari jenazah ayah. Saya menyembul dan menyelam di antara jenasah-jenasah itu, mencoba mengingat kembali baju apa yang dipakai ayah. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hujan yang sangat deras menyebabkan permukaan air sungai penuh uap. Saya megap-megap. Saya berenang menepi setelah usaha saya sia-sia.
Mayat-mayat embun, taruhlah di nampan, jadi hidangan suci dari bau tangan yang gatal. Menyayat-nyayat dada, menyayat-nyayat air liur yang dijilati petir. Mayat-mayat yang menyembunyikan nama, watak, kelakuan, pekerjaan, emosi, elan vital. Mayat-mayat, puluhan, ratusan ribu, carilah dalam map dari para pencari data. Para pencari data yang berdatangan dari seantero dunia.
Memanggili ayah, memanggili nama dari halaman yang hilang. Mayat-mayat yang begitu mengerti mengantarkan kepala-kepala yang timbul tenggelam dalam air. Saya tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa mengerti.
Yang mana tubuh ayah? Yang mana jenazah ayah? Saya mengikuti terus tumpukan mayat-mayat itu yang terus diseret sungai sampai menuju entah. Saya berlari terus, saya berlari terus, saya berlari terus . . .
Hari-hari yang sangat berat bermunculan. Hari-hari yang sangat berat yang harus kami panggul. Saya dikeluarkan dari pekerjaan saya sebagai pemasar barang-barang kebutuhan dapur karena dianggap tidak bersih lingkungan. Begitu juga kakak perempuan saya, Retno, guru SMP. Masih untung, adik saya, Ning, yang bekerja di sebuah usaha kerajinan rakyat, alhamdulillah, masih boleh bekerja. Mungkin karena Ning masih kecil. Sementara itu uang tabungan ibu semakin menipis.
Waktu itu kabar merebak, ikan-ikan yang harganya masih murah sebagai lauk, mulai ditinggalkan karena di dalam tubuh ikan-ikan itu biasa ditemukan potongan jari, bola mata, usus, maupun barang-barang yang menempel di tubuh-tubuh mayat yang memenuhi Sungai Brantas.
Kami masih bertahan makan ikan karena harganya semakin murah, sampai ibu menemukan cincin kawinnya yang dipakai di jari ayah. Hari-hari semakin bertambah berat bagi kami bertiga yang semakin lemah menjalaninya, ketika kami merawat ibu yang koma satu minggu lamanya dengan makanan seadanya yang sangat tidak pantas dan menguburkannya pada hari ke delapan.
Kami bertiga menangis dengan airmata yang menusuk-nusuk hulu hati, mengantarkan jenazah ibu yang diusung oleh para tetangga yang kasihan melihat penderitaan kami. Di gundukan kuburan itu, Ning menangis sejadi-jadinya sambil mencakar-cakar tanah gundukan.
Beberapa bulan kemudian merupakan hari-hari teror dan horor menghantui kami karena di waktu dini hari kami sering terbangun dari tidur terkaget-kaget oleh gedoran orang-orang. Mereka merangsek masuk mencari buron. Mengoprak-oprak kamar tidur kami, memeriksai kolong tempat tidur, dipan, lemari pakaian, dapur, plafon, maupun kebun belakang. Sering Ning terbangun dari tidur menjerit-jerit memanggil ayah, memanggili ibu. Baru reda setelah dipeluk Retno. Sungguh saya tidak bisa mengerti mengapa kami kecebur dalam kubangan begini rupa tetapi kami harus bertahan atau kami hancur berantakan. Saya bekerja serabutan. Apa saja saya kerjakan untuk bisa bertahan hidup. Termasuk jadi tukang sapu pasar.
Hari-hari yang mengerikan itu sering mendorong nyawa kami sampai di tenggorokan. Nyawa yang digondeli raga sekuat-kuatnya. Supaya tidak terlepas. Supaya tetap betah menghuni di dalam tubuh kami dalam keadaan sengeri apa pun. Duh, raga, gondelilah nyawa.
Rasanya tubuh kami tinggal kulit pembalut tulang. Kecantikan Retno yang mewarisi kecantikan ibu, lenyap. Retno tinggal kering kerontang, tanpa seyum, tanpa harapan. Begitu juga Ning yang tampak lebih cantik dari kakaknya, persis anak gelandangan yang memakan apa saja supaya perut tidak lapar. Segala puji bagi Allah Yang Maha Suci, kami masih memiliki rumah tempat kami berlindung dan tempat kami menangis sepuas-puasnya.
Diam-diam saya sering mengunjungi kuburan ibu. Saya tumpahkan segala unek-unek sambil berlelehan air mata. Juga saya mendoakan ibu semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengaruniai ibu kebahagiaan di akhirat. Kadang saya merasa ibu hadir di samping saya yang membuat saya menangis sejadi-jadinya.
Saya juga sering menapak-tilasi tempat ayah terduduk di tepi sungai bersama puluhan orang sebelum dieksekusi. Saya meraba-raba pasir yang mungkin keringat dari kaki ayah masih tersisa. Saya memeluk dan menangisinya sambil memohon Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengaruniai ayah kenyamanan di akhirat.
Ayah adalah kepala SMP. Semua kegiatan ayah berkisar antara rumah dan sekolah. Hampir tak pergi ke mana-mana. Jika sekolah piknik, ayah tak pernah ikut. Ia menugaskan guru yang lebih muda. Ayah cukup berbahagia mendampingi ibu yang sibuk dengan usaha kateringnya. Ayah tak tertarik politik. Beliau murni seorang pendidik. Setiap kali saya terbangun tengah malam atau dini hari, ayah dan ibu tampak sedang khusyuk beribadah yang membuat saya malu hati karena siapa tahu sedikit banyak sapuan ibadahnya juga untuk keselamatan hidup saya, seorang anak yang barangkali saja tidak memiliki dimensi spiritual, kurang bersyukur, tak menyadari dilahirkan oleh sepasang orang tua yang selalu menginjakkan kakinya di halaman surga, di mana tak semua orang mampu pergi ke sana.
Sampai malam malapetaka itu mengetuk pintu rumah kami dan membawa ayah pergi. Untuk sesaat, saya, ibu, Retno, dan Ning tertegun, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang menggelandang ayah begitu garang, juga tak bersedia memberi alasan.
Beberapa tetangga yang ikut jadi korban berkumpul di rumah kami, saling bertanya boleh jadi di antara kami ada yang jauh lebih mengerti akan situasi yang terjadi.
Di rumah kami inilah semuanya bertangis-tangisan meluapkan kesedihan masing-masing, seperti gaung yang tak henti-hentinya, tak bisa dimengerti, tak bisa dimengerti, tak bisa dimengerti . . .
Yang saya takutkan setelah meninggalnya ibu, Retno dan Ning tergoncang jiwanya sehingga menjadi tidak waras. Saya ikuti terus perkembangan jiwa keduanya. Saya cukup lega, keduanya cukup sehat, hanya saja kesehatan Retno dari hari ke hari terus memburuk.
''Bertahanlah, Retno,'' bisik saya di telinga Retno yang membujur kaku dan panas. ''Jangan kecewakan ayah dan ibu. Jangan bikin ayah dan ibu menangis di dalam kuburnya. Kamu harus bangun dan bekerja. Kita bertiga harus bekerja supaya ayah dan ibu bangga.''
Ning memeluk erat-erat Retno sambil menangis keras-keras.
Setelah sakit beberapa lamanya, Retno muntah darah. Karena ketiadaan obat dan makanan yang baik, akhirnya Retno meninggal.
Retno saya kuburkan di samping kuburan ibu. Setiap hari saya kunjungi kuburannya yang menyadarkan saya bahwa saya telah gagal menyelamatkan keluarga kecil ini. Apalagi Ning pergi meninggalkan saya entah ke mana.***
Tangerang, 20 Januari 2008


.jpg)

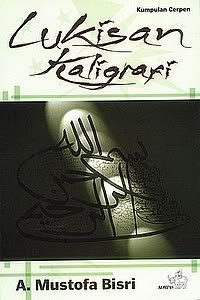

Tidak ada komentar:
Posting Komentar