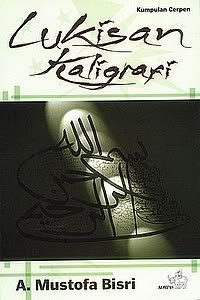Selasa, 16 Desember 2008
Langkah Oktavia
02.07.2008
» Walaikumsalam wr.wb. insyallah dak apa-apa
» puisinya maksudnya apa ya? Boleh saya tahu nama dan jurusan
» tapi untuk apa puisi di tulis jika tidak di mengerti pembacanya“ bagi saya puisi memang seni. Akan tetapi pencerahan baru bisa kita dapatkan setelah kita terlebih dulu mengerti artinya. Coba di cerna dulu ya
» Ya udah selamat malam.. jika jawaban saya kurang berkenan. Mungkin kamu lebih paham tentang makna puisi lebih dari saya. Sekali lagi maaf J
04.07.2008
» Waalaikumsalam wr.wb. segala pujian hanya untuk Allah.. emh... saya ndak cantik... jangan-jangan kamu salah orang :-)
»
» Orang satra pinter buat puisi ya? Saya bisa di buatkan puisi satu bait? Boleh, maaf kalo merepotkan.
» Kira-kira saya kenal tidak ya denagn kamu? Puisinya bagus banget, tapi kalau disuruh mengartiakn kamu past tidak berkenan. Tidak apa-apa J.
» Amin... oia kamu tadi berpuasa tidak? Puasa Rajab ni... Saya lagi di Kota Solo, buat menjernihkan pikiran dan hati. Kamu anak mana?
» Ya tidak apa-apa ... masih ada waktu, kan masih 29 hari lagi rajabnyaJJ Jawa Timur mana ya? La kok ndak dari dulu-dulu kenal ma saya. Kok saya sudah gak di Surabaya baru kenalan?
» Ya kamu tidur dulu aja... Saya masih pengin melihat bintang, mumpung bintangnya banyak banget ... J Besok kalau kamu masih bantu paman mu kamu ndak usah puasa dulu. Kalu dah longgar baru kamu puasa. J.
05.07.2008.
» Bismillah. Hidup ini kadang membawa kita pada titik diman kita tidak ingin berada di sana. Pada titik yang begitu jauh dari dari harapan. Tapi bertahan dan mencari jalan yang terbaiuak harus dilakukan. Sebut nama Allah dalam kelemahan dan kelelahan. Karena dialah sang pemberi ujian, pemberi kehidupan, dan pemberi pertolongan.
» Ya.. benar.. Usaha dan doa harus seimbang... memangnya kamu teman akrab faruk? J.
» Ehm gitu... Saya belum tahu kamu, ya dah gak apa-apa... ntar kapan-kapan juga tahu sendiri... Betul kan?
07.07.2008
» Afwan... Tadi Hp saya dibuat mainan adik sepupu saya... mungkin salah pencet... dari tadi saya tidak pegang Hp soalnya. Afwan3X.
» Afwan. Memangnya SMSnya apa sih? Dia masih TK.. ada pertanyaan apa? Saya semakin bingung dengan kamu?
08.07.2008
» Wassalamualaikum wr.wb. Saya tidak mengerti maksudnya apa? Muangkin akhi tahu saya punya prinsip, tidak akan pacaran... Saya menjaga hati untuk tidak pacaran selam 21 tahun.
» Saya berpilir dan memutuskan untuk menjaga hati saya kembali... Sampai saya siap dan yakin Allah lah yang memberikan yang terbaik untuk saya... sekarang saya harus fokus untuk ke kerja dulu.
10.07.2008
» Wassalamualikum wr.wb. saya mendoakan semoga kamu mendapatkan akhwat yang lebih baik dari saya... Karena saat ini saya benar-benar hanya ingin membahagiakan ayah saya... Maafkan saya semoga Allah mengampuni saya.
» Arfan tidak marah ataupun kecewa kan dengan keputusan saya? Mau kan memaafkan saya? Bukan egois namun ini merupakan keputusan yang terbaik...
» Kamu orang baik, Arfan. Semua orang yang menjadi teman okta insyAllah baik... Arfan harus berhasil untuk semuanya... saya yakin, suatu saat kamu bisa temukan akhwat yang benar-benar dah siap.
11.07.2008
» Wassalamualikum wr.wb. ndak apa-apa, Arfan tenang aja ... FS nya tidak tidak apa-apa kok... J.
» Ndak, perbuatannya mungkin lagi khilaf aja teman-teman kamu... Maaf juga saya buka FS kamu secara tiba-tiba. Kamu ndak marah kan sama saya?
20.07.2008
» Wassalamualikum wr.wb. Maaf baru balas, tadi ada rapat si LBB... alhamdulillah kabar baik.
» Buku apa ya? Siapa yang nulis?
» Ya, selamat juga ... kelas Saya kemarin ada juga rencana gitu, tapi ndak bisa kayaknya... jadi teman-teman sekelas saya suruh mengisi di diari milik saya. Tapi sekarang diarynya di bawa siapa tidak tahu.
» Ya, jangan main terus, skripsinya cepat diselesaikan. Teman. Wassalamualikum.
05.08.2008
· Bismillah, Kamu belum mengenal saya… saya tak sebaik yang kamu pikirkan… (…)
· Saya tahu itu hanya perasaan kamu sesaat, ntar… juga hilang sendiri… saya paham itu J lupakan saya dan kembalilah pada kehidupanmu sediakala.
· Di hati saya sudah ada senja impian saya. Dan saya ingin menunggu dia.
· Saya tidak mau memberi harapan atau mengecewakan siapa pun.
· Arfan, kamu boleh sms saya lagi kalau kamu sudah menganggap saya sebagai teman biasa… sama seperti faruk, angga, dll. Senja itu impian saya biarkan diaya bersinar.
~untuk Oktavia yang pertama
via, kusebut cahayamu lentera biru,
juga pipit di pantai kemarau.
sedang aku bamboo yang menua.
Sendiri menanti hingga mati dalam sepi.
Sebab sajak ini terlalu takut.
Hingga ia lirih merintih memanggilmu.
kemarilah. karena hanya sisipus
yang mengulangi kesalahannya
Desember, 2007
MUKA IBU KOTA
mulai mengeropos dan keringat begitu sengat. Maka,
malam begitu lelap, hanya bulat berbalut senyap.
Bahkan bukan hanya malam yang senyap. Tapi,
cahaya enggan padat merayap. Jingga dalam waktu yang terlelap.
Tapi senyumnya begitu menyiksa. Ketika
anai-anai beraganti riang canda seluruh desa.
Pasti disini dan tetap disini.
Tiang harapan begitu tinggi.
Hingga melampau tiang upacara senin pagi.
Hingga akhir perjamuan suatu pagi menanti dengan pasti.
Juni, 2008
SENJA DAN GERIMIS
Seperti kuning bulir Padi, yang menanti gerimis
di akhir Mei. Yang terselip senyum petani. Pasti aku
akan sabar dan tetap menekur, membisu menanti.
Hingga lupa mengeja huruf o dan a di waktu pagi.
Bahkan jika haus menusuk tenggorokanmu, maka akan kubasuh
dari tetes embun yang menyelimuti pucuk-pucuk daunmu. Juga dari kakimu.
walau punggung ini kelu, sampai malam
menusuk sumsum tulang yang mambiru.
Tapi, aku adalah senja di akhir Mei,
yang menanti datangnya gerimis juga pelangi.
Walau bisu dan sepi, tetap aku setia
Seperti kesetiaan malam yang menyapa cahaya fajar pagi.
Juli, 2008
Selasa, 28 Oktober 2008
STA dan Novel-novelnya

IGNAS KLEDEN
Pada 29 Mei 2008 Akademi Jakarta menyelenggarakan STA Memorial Lecture di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Salah satu pemberi kuliah adalah Ignas Kleden, khusus menyoroti Sutan Takdir Alisjahbana dengan novel-novelnya. Novel Kalah dan Menang tidak dimasukkan ke dalam pembahasan di sini karena penulis belum selesai membacanya ketika menulis esai ini. Lembar Bentara menyiarkan kuliah Ignas tersebut dalam dua penerbitan. Bagian pertama pada terbitan hari ini. Bagian kedua pada terbitan Agustus. Untuk keperluan penerbitan ini, semua anotasi dihilangkan.
Tahun 1950 Asrul Sani mengajukan kritik bahwa Sutan Takdir Alisjahbana (seterusnya: STA) adalah seorang guru dengan banyak jasa, tetapi kedudukannya secara artistik tidak kita ketahui. Posisi dan pendirian kesenian STA tidak begitu jelas, tidak sejelas pendiriannya tentang pendidikan dan kebudayaan misalnya.
Asrul memang agak berlebihan karena pendirian STA tentang sastra sangat jelas dalam esai-esainya, misalnya dalam pandangan yang secara kategoris membedakan puisi lama dan puisi baru; tetapi pendirian itu tidak begitu jelas kalau diimplementasikan dalam karya sastra yang dihasilkannya sendiri, khususnya dalam penulisan novel.
Berulang kali dikatakan bahwa sastra tidaklah bisa bermewah-mewah dengan keindahan untuk mencapai kepuasan seseorang dalam mencipta, tetapi harus dilibatkan secara aktif dalam seluruh pembangunan bangsa, meskipun kata pembangunan itu sendiri belum banyak digunakan pada masa STA memaklumkan pendirian-pendiriannya.
Dalam esai yang sama Asrul juga menulis bahwa STA termasuk dalam generasi yang sibuk dengan kesusastraan amtenar. Dikatakan secara sosiologis, STA hanya memerhatikan kesusastraan kelas menengah yang dipenuhi para guru, dokter, wedana, gadis cantik, dan barangkali juga mertua yang kaya dan memaksakan kehendak.
Pernyataan-pernyataan Asrul tersebut seakan meramalkan masa depan penulisan novel STA, tetapi tidak seluruhnya benar kalau kita mengikuti penulisan novel STA semenjak awal. Perlu ditambahkan bahwa apa yang tak seluruhnya benar ini tidak hanya berlaku bagi pernyataan Asrul, tetapi juga pada pernyataan-pernyataan STA sendiri. Kalau sastra dan seni umumnya dianggap harus membuat orang lebih optimistis dan menghadapi kehidupan dengan semangat juang yang tinggi untuk mengatasi berbagai masalah dan situasi kritis, maka keinginan STA tersebut tidak juga terlihat pada beberapa novelnya.
Dalam novel Tak Putus Dirundung Malang, misalnya, kita bertemu dengan dua bersaudara, Mansur dan Laminah, yang sepanjang hidupnya selalu mengalami kesulitan dan nasib sial, dan seakan keduanya tak berdaya mengatasi kesialan tersebut. Kesulitan-kesulitan dilukiskan sebagai kondisi-kondisi obyektif yang tidak bisa diatasi oleh keduanya dengan kemauan dan kekuatan sendiri. Novel ini bertentangan dengan keinginan STA karena cenderung memperlemah semangat, membuat orang mengucurkan air mata, tetapi tidak melecut orang untuk berjuang dengan gembira menghadapi dunia.
Juga, ini bukanlah novel yang melukiskan dunia amtenar, tetapi dunia orang-orang kecil yang terlunta-lunta nasibnya, tanpa kesempatan untuk menaiki tangga mobilitas sosial yang menjadi ciri utama dari kehidupan kelas menengah.
Kecenderungan STA seperti ini terlihat juga dalam novel Dian yang Tak Kunjung Padam. Ini cerita tentang romantisisme si pungguk merindukan bulan. Tema utama adalah masalah yang muncul dari jarak sosial karena perbedaan keturunan, perbedaan kota desa, dan perbedaan kelas ekonomi. Novel ini pun penuh dengan suasana sedih diselang-selingi peristiwa-peristiwa melodramatis.
Novel lainnya berjudul Anak Perawan di Sarang Penyamun berisi cerita yang secara psikologis hampir mustahil karena seorang anak dara ditangkap dan dibawa ke teratak penyamun setelah orangtuanya dirampas hartanya dalam suatu perjalanan. Ayah gadis itu, Haji Sahak yang kaya, mati dalam perampokan itu, dan ibunya yang selamat menjual rumahnya yang besar di Pagar Alam, dan kemudian hidup miskin di sebuah pondok di ujung kampung.
Setelah suatu perampokan yang gagal dan menewaskan beberapa rekannya, kepala penyamun itu, Medasing, dapat diyakinkan oleh si Sayu, gadis itu, untuk pulang ke Pagar Alam dan hidup sebagai orang baik-baik. Ibu Sayu meninggal ketika berjumpa lagi dengan anaknya itu, dan cerita tidak diteruskan sampai tiba-tiba pembaca diberi tahu bahwa Pagar Alam diperintah oleh seorang hartawan yang bijaksana dan istrinya yang cantik jelita dan pemurah. Hartawan tersebut adalah Medasing, bekas kepala penyamun, dan istrinya tentulah Sayu, perempuan yang termasyhur kecantikannya di seluruh Pagar Alam.
Hal yang tak meyakinkan ialah bahwa selama berada dengan para penyamun di teratak mereka di tengah hutan rimba, Sayu, dara yang jelita itu, tak sedikit pun menarik hati para penyamun itu, kecuali informan yang bolak-balik dari desa ke hutan untuk memberi kabar tentang orang kaya yang akan lewat dan dapat dijadikan mangsa perampokan. Pengarang memberi keterangan bahwa para penyamun itu terlalu lama hidup di hutan, hampir tak mengenal perempuan, dan perhatian mereka hanya tertuju kepada pembinaan tenaga fisik untuk menyabung nyawa dalam tiap perampokan. Inilah sebabnya, mereka tidak belajar tertarik kepada seorang wanita selagi berada di rimba.
Dapat dipastikan bahwa ketika menulis novel tersebut, STA belum banyak membaca buku-buku psikologi, khususnya psikologi yang menyangkut kehidupan seksual. Pengarang tampaknya belum mengenal teori-teori Freud, yang menjelaskan bahwa dorongan seksual bukanlah sesuatu yang dipelajari dari masyarakat, tetapi berasal dari suatu tenaga yang disebut ID, yang tumbuh bersama kematangan psikofisik seorang individu. ID tidak bersifat baik atau buruk dan sering bekerja secara tidak disadari oleh manusia.
Masyarakat dan norma-normanya menjadi SUPEREGO, yang harus menjaga agar tenaga tersebut tidak merusak kehidupan EGO. Dengan demikian, mengatakan bahwa para penyamun itu tidak tertarik kepada gadis jelita, Sayu, karena berada jauh dari masyarakat adalah keterangan yang tidak meyakinkan secara psikologis karena ID sebagai energi selalu aktif apakah seorang berada di desa, di kota, di hutan rimba, dan bahkan kalau seorang berada seorang diri di kamar atau di tepi pantai.
Kalau novel ini bermaksud mendidik pembaca agar menghormati kaum perempuan, maka inilah contoh soal tentang pendidikan yang memberikan ilusi karena tidak berdasarkan pada kenyataan dan hanya berdasarkan angan-angan pengarang yang tidak bisa dibenarkan dalam kehidupan manusia.
Ketiga novel tersebut rupanya ditulis ketika paham STA tentang sastra yang mendidik belum matang dalam pemikirannya. Ketiga novel itu adalah sanggahan dalam praktik literer terhadap apa yang dikehendaki oleh STA tentang peran sastra dan seni dalam mendidik masyarakat, dan menyanggah pula kritik Asrul Sani bahwa novel-novel STA adalah sastra amtenar, sastra kelas menengah, atau sastra borjuis.
Sifat amtenar dalam novel STA baru muncul dalam novel Layar Terkembang karena lingkungan tempat cerita itu bermain adalah lingkungan amtenar. Tokoh utama cerita itu adalah sepasang gadis bersaudara bernama Tuti dan Maria, anak bekas wedana Banten, Raden Wiraatmaja, yang melewatkan masa pensiunnya di Jakarta. Maria adalah siswa HBS dan Tuti sudah bekerja dan aktif sebagai orang pergerakan yang turut memimpin organisasi perempuan bernama Puteri Sedar. Lingkungan pergaulan mereka adalah siswa dan guru-guru Belanda di satu pihak dan orang-orang pergerakan di lain pihak.
Maria jatuh cinta kepada Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran di Jakarta, yang sedang menyiapkan ujian doktoralnya. Ayah Yusuf adalah demang Munaf di Martapura di Sumatera Selatan. Maria, gadis santai yang agak manja, suka akan kembang dan tanam-tanaman, membaca buku-buku tentang cinta, dan gemar akan baju-baju bagus yang dipilih dengan selera tinggi. Tuti, kakaknya, tampil sebagai perempuan intelektual yang sibuk dengan buku-bukunya, tegas dalam sikap-sikapnya, dan terlibat aktif dalam pergerakan untuk memajukan kaum perempuan.
Yusuf memang jatuh cinta kepada Maria dan keduanya saling merindukan setiap saat. Meski demikian, dia sangat menghormati dan mengagumi pikiran dan pendirian Tuti, serta terkesan oleh sikapnya yang pasti dan penuh komitmen kepada cita-cita kaum perempuan.
Munculnya Yusuf dalam kehidupan dua gadis bersaudara itu menimbulkan efek berbeda. Maria merasa menemukan lelaki idamannya, dan tanpa ragu bersedia menyerahkan diri sebagai istrinya, apabila pelajaran keduanya telah selesai. Tuti dalam pada itu tetap dengan kesibukan dan cita-citanya, tetapi pada waktu-waktu tertentu merasa terganggu juga oleh kemesraan yang diperlihatkan Maria dan Yusuf.
Betapa pun pengarang terlihat sangat mengunggulkan Tuti, pada akhir cerita ternyata Tuti dapat ditaklukkan oleh tuntutan cinta ketika Maria yang mengidap penyakit TBC yang tak dapat disembuhkan menyampaikan amanat kepada Tuti dan Yusuf agar keduanya jangan mencari peruntungan pada orang lain, tetapi saling menerima sebagai pasangan yang saling mencintai.
Akhir cerita ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Kepada pembaca tidak dijelaskan bagaimana Tuti yang keras hati dapat dengan mudahnya menerima permintaan adiknya untuk menjadi calon istri Yusuf dan apakah Tuti yakin kalau setelah menikah nanti, Yusuf masih menghormati cita-cita dan perjuangannya untuk kaum perempuan.
Hal ini perlu dipertanyakan karena masalah inilah yang menyebabkan Tuti telah menolak cinta dua laki-laki sebelumnya. Demikian pula Yusuf, apakah dia menerima Tuti karena menghormati permintaan Maria atau semata-mata karena merasa kasihan kepada Tuti? Ataukah sudah semenjak awal hatinya terbelah dua antara Maria dan Tuti meskipun hal ini tak terlihat dalam teks-teks novel ini?
Akhir cerita memang mengharukan, tetapi pertanyaan-pertanyaan tersebut tak memperoleh jawabannya. Akibatnya, ketika layar itu terkembang, tidak jelas pula apakah yang terkembang adalah cinta antara laki-laki dan perempuan ataukah terkembang cita-cita tentang meningkatnya martabat kaum perempuan yang dengan gigih diperjuangkan Tuti sebelumnya.
Dari sastra amtenar dalam Layar Terkembang STA meningkat menulis sastra yang benar-benar borjuis dalam Grotta Azzurra. Ini novel tentang orang-orang yang tidak pernah lagi mengalami persoalan uang dan masalah basic needs, tetapi yang tiap hari berdiskusi tentang berbagai topik politik, seni, filsafat, dan pandangan hidup di kota-kota di Eropa. Diskusi berlangsung dalam perjalanan wisata, atau di rumah seorang kenalan dengan makanan berlimpah disertai berbagai jenis anggur, di restoran hotel-hotel berbintang, atau di sebuah galeri tempat para pelukis memamerkan lukisan-lukisan.
Tokoh utama dalam novel ini adalah Ahmad, seorang pelarian politik anggota Partai Sosialis Indonesia, yang terlibat dalam pemberontakan melawan pemerintahan Soekarno, dan kemudian bertahan hidup di kota Roma dengan bekerja pada sebuah pabrik mobil. Dia berkenalan dengan Mercelin Janet, seorang perempuan 35 tahunan, berasal dari Paris, anak seorang profesor kesenian antik dan Abad Pertengahan. Keduanya berkenalan dengan dua orang lainnya, yaitu Conrad Weber, profesor ilmu politik dari Frankfurt, dan Evelin Turner, seorang perempuan Amerika, yang bekerja untuk tentara Amerika pada dinas hubungan tentara dan masyarakat di Frankfurt.
Ahmad dan Janet bertemu secara kebetulan ketika mereka naik kapal dari Sorrento ke Pulau Capri untuk melewatkan liburan di sana. Perkenalan mereka menjadi lebih dekat ketika keduanya mengunjungi sebuah goa yang terkenal karena airnya yang berwarna seperti zamrud hijau biru. Nama novel itu diambil dari goa itu yang dinamakan Grotta Azzurra (goa biru). Kisah cinta antara Ahmad dan Janet memang berkembang, bersama dengan hubungan yang semakin mesra antara Conrad dan Evelin.
Hal yang mengganggu ialah bahwa entah di Pulau Capri, di Napoli dan Firenza, atau di Frankfurt dan Lindau, kisah mereka bagaikan hanya sampiran untuk hal yang lain sama sekali, yaitu diskusi-diskusi yang panjang dan berlarut-larut tentang sejarah para kaisar Roma, tentang kesenian Romawi kuno, kemudian tentang partai komunis Italia dan peranan politiknya, tentang seni renaisans dan seni modern, tentang seks bebas dan perkawinan, tentang emansipasi perempuan dan agama, atau tentang perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Abad Pertengahan dan di zaman modern.
Memang mengagumkan melihat bagaimana pengarang menyiapkan diri dan bahan-bahannya tentang berbagai soal itu. Akan tetapi, soal-soal itu ditonjolkan sedemikian rupa sehingga seakan-akan menjadi kuliah privat yang diberikan oleh Janet kepada Ahmad atau Evelin kepada Janet atau Ahmad kepada Conrad. Lingkungan sekitarnya menjadi tidak penting. Akibatnya, kalau kita membuang semua tempat itu dari teks, maka diskusi-diskusi itu tetap berjalan dengan baik.
Sebagai contoh saja, di Pulau Capri hanya diceritakan tentang hotel tempat Ahmad dan Janet menginap, tentang pemandangan-pemandangan indah yang membangkitkan lagi hasrat melukis Janet yang telah mati bertahun-tahun, dan kemudian tentang diskusi-diskusi keduanya. Tak sepatah kata pun diceritakan kehidupan penduduk di Italia selatan yang terkenal miskin, dan bagaimana penduduk di sana berjuang untuk mempertahankan hidup mereka.
Demikian pun Ahmad diceritakan sudah mempunyai istri dan tiga orang anak, dan keluarganya inilah yang menjadi ikatan yang membuatnya selalu ragu untuk mengikat dirinya dengan Janet dalam hidup bersama di kota Paris, sebagaimana diinginkan oleh Janet, tetapi tidak kesampaian. Sayangnya, kita tak diberi informasi apa pun tentang keluarganya ini di Indonesia: apakah istrinya bekerja atau tidak, berapa usia anak-anaknya, apakah mereka anak laki atau perempuan, dan apakah mereka masih mengingat nama dan wajah ayah mereka. Bahkan nama istrinya pun tidak kita ketahui.
Ini bukanlah suatu strategi dalam bercerita, tetapi lebih merupakan kealpaan pengarang yang hanya sibuk dengan ide-idenya dan menjadikan semua konteks tidak sebagai setting cerita, tetapi hanya sebagai back drop yang boleh dibongkar pasang setiap waktu tanpa mengganggu jalannya diskusi.
Memang beberapa kritikus menamakan novel ini novel ide, tetapi persoalannya apakah ide itu digarap di sebuah ruang kuliah, dalam seminar akademis, atau dalam sebuah cerita. Di sinilah kesulitannya. Hal ini tidak diperhatikan dan bahkan tidak dipedulikan oleh pengarang. Akibatnya, buku ini akan berguna dan mengasyikkan kalau dibaca sebagai sebuah buku pengantar pelajaran tentang berbagai soal, tetapi susah dibaca sebagai sebuah novel yang menarik.
IGNAS KLEDEN Sosiolog
KOMPAS, 11 juli 2008
Anugerah Pena Kencana; oleh
Pemberian anugerah karya sastra di Tanah Air bukan kali ini saja yang panen kritik, tapi sudah berulang-ulang seiring bergulirnya anugerah. Contoh yang sangat dekat ialah KLA (Katulistiwa Literary Award), SEA Write Award, dan sebagainya.
Tradisi kritik memang sudah mendarah daging di negeri ini. Tetapi, ''tradisi'' tersebut muncul tersebab ''budaya'' kita juga yang kerap abai pada aturan-aturan yang telah disepakati. Atau longgar dan menyepelekan persyaratan yang sudah diteken; aji mumpung dan menganggap masyarakat dapat ''dipaksa'' untuk menyetujui setiap keputusan yang diambil.
Sampai kini KLA tak sepi oleh kritik. Misalnya, soal penjurian tingkat awal untuk ''memburu'' buku-buku sastra di toko buku (konon, prioritas TB Gramedia) yang ada di Jakarta. Mereka ''dimodali'' untuk membeli sejumlah buku, kemudian mengajukan judul buku yang dipilihnya untuk mengikuti penyaringan.
Sampai di sini, kelihatannya tak ada masalah. Pertanyaan pun lalu muncul: siapa (mereka) yang dipercaya penyelenggara untuk memburu buku sastra? Berapa ''modal'' yang diberikan kepada mereka dan dengan modal itu berapa buku yang harus dibeli dan dibaca. Apakah panitia mengaudit modal dan buku yang dibeli? Sikap ''saling percaya'' rasanya tidak tepat dilakukan di sini.
SEA Write Award yang ditaja Pusat Bahasa juga tak terelakkan menuai kritik. Bahkan acap sulit diterima akal, kenapa si Fulan mendapat SEA Write Award tahun ini dan mengapa si Bolan yang nyata-nyata buku-buku karyanya --secara kuantitas dan kualitas-- dapat dipertanggungjawabkan, justru tidak terpilih? Sebab itu, SEA Write Award lalu dianggap ''anugerah arisan'' karena memang yang sudah pernah mendapat tidak akan mendapat lagi. Seorang teman tatkala memeroleh anugerah itu, melalui pesan pendek, dengan gurau berujar: ''Kali ini giliran aku yang mendapat arisan.''
Itulah sedikit gambaran fenomena award-award di ranah sastra Tanah Air. Sebenarnya masih banyak, termasuk Ahmad Bakrie Award, Akademi Jakarta, dan seterusnya. Pemberian anugerah sama tipisnya dengan penetapan sastrawan yang (akan) diundang ke luar negeri: sama-sama berisiko dikritik dan sama-sama ''bermain''.
Ya! Bicara soal ''bermain'' memang kehidupan ini adalah permainan. Karena permainan, lakoni saja dengan penuh keriangan. Dengan kata lain, gak usah serius amat, bermain-main saja, santai. Meminjam moto konco-konco di KoBer (Komunitas Berkat Yakin): rock n roll hahaha.
Lalu, apakah karya sastra bukan lahir dari keseriusan? Soal ini, siapa pun setuju 100 persen. Antara karya sastra dan penilaian award acap tak dapat dicari titik temu dan titik tujunya. Lha wong sekelas Nobel saja tak bebas kritik, kok.
Aturan-aturan dalam penentuan suatu pilihan dibuat sangat ideal. Tetapi, seideal apa pun tetap punya celah untuk ''dimainkan'', lalu jadi ''ketetapan baru''. Undang-undang, AD-ART, dan apa pun namanya selagi yang buat manusia, ia punya ruang untuk dilanggar.
Demikian pula dengan Anugerah Sastra Pena Kencana (ASPK) 2008. Setahu saya dari milis-milis, puisi-puisi Joko Pinurbo -penyair yang juga salah seorang dewan juri ASPK-- melanggar deadline antara pemuatan di koran dan kesepakatan dalam penjurian (Maafkan kalau apa yang saya kemukakan ini salah).
Tulisan ini tak akan jauh memasuki masalah puisi-puisi Jokpin. Saya --dan barangkali banyak pembaca sastra-- hanya mempertanyakan kepatutan apa sehingga para juri juga berhak menilai karyanya? Pertanyaan ini kita sempitkan saja: pantaskah juri merangkap menjadi peserta, meskipun berdalih juri tersebut tak ikut menilai ketika karyanya diajukan; artinya juri-juri lain yang menilai, dan seterusnya.
Kelihatannya tak ada masalah. Namun, sesungguhnya di situlah masalahnya. Analoginya demikian: puisi Fulan (bukan juri) dinilai oleh seluruh juri, sedangkan puisi Bolan (kenetulan juga menjadi juri) dinilai juri lain (minus dirinya). Kenetralan dirinya --kalau mau dikatakan netral-- sekaligus berpihak. Betapa tidak, ketidakikutsertaan dalam menentukan karyanya sendiri, sesungguhnya ia sudah memberi nilai pada karyanya. Tinggal teman-teman jurinya yang lain yang memberi bobot atas karyanya. Adilkah itu, dan di mana keadilannya?
Lalu, kritik yang juga meruak adalah ihwal karya-karya dari panitia yang lolos dalam buku tersebut. Rupanya panitia juga tak hendak dipisahkan dirinya sebagai kreator. Karena itu, dia ''minta keadilan'' agar karyanya ikut dalam bursa pemilihan. Soal ini juga kelihatannya tidak bermasalah. Para panitia akan berdalih: sebagai sastrawan karya kami juga punya hak untuk dinilai, dan jangan dikaitkan statusnya sebagai kreator dan bagian dari penyelenggara. Jika dalih ini terus dipelihara, bisa sangat berbahaya. Bagaimanapun kedekatan emosional antara panitia, juri, dan sebagai kreator tidak bisa dianggap sepele.
Kritik lain, saya pernah dikirimi pesan pendek dari seorang sastrawan Riau. Ia meragukan keakuratan saat perekrutan karya-karya yang terpublikasi setahun berjalan itu dari bebagai koran di sejumlah kota di Tanah Air. Pasti ada yang luput. Ia ambil gampang saja. Satu koran akan menurunkan beberapa puisi dan satu cerpen setiap pekan. Dikalikan setahun, jadilah 48 kali terbit (tak termasuk hari libur yang mungkin bertetapan pada Minggu). Lalu dikalikan minimal 5 puisi atau 7 puisi. Jadi, untuk satu koran saja, setahun bisa menginventarisasi sedikitnya 240 puisi. Nah, berapa koran yang ditelisik panitia ASPK? Dan, apakah setiap pekan dari media-media yang ditetapkan panitia tersebut dijamin tidak akan luput dari penyaringan panitia?
Seorang penyair lain berkelakar, ASPK tak lebih hanyalah ''permaianan''. Ia sepakat dengan contoh-contoh seperti yang sudah dikemukakan di atas. Itu sebabnya, teman penyair itu --kebetulan karyanya masuk dalam 100 Puisi Pilihan ASPK 2008 mengaku tak tetarik mengikuti babak pilihan pembaca buku itu melalui SMS (short message system).
Dari awal saja sudah permainan, karena itu tak perlu serius-serius amat, teman penyair itu menegaskan. Sebab, kalau kita mau ikut dalam permainan itu, kudu punya modal.
Sampai di sini, kita berkalkulasi dengan modal. Harga buku karya ASPK 2008 Rp 50 ribu per eksemplar. Sekiranya memiliki modal Rp 30 juta, kita akan mengantongi minimal 600 suara. Kalau menang, masih untung Rp 20 juta. Sebab, pemenang anugerah ini mendapatkan Rp 50 juta. Lumayan kan? Namun, dengan perolehan suara yang cuma 600 itu belum apa-apa. Posisinya masih gambling. Karena itu, perlu siasat lainnya: mengontak saudara, teman, kolega, dan seterusnya agar bersedia memberi dukungan.
Mari berandai-andai. Penyair Fulan kebetulan seorang karyawan (lebih baik lagi karyawan yang memunyai jenjang komando semisal di kepolisian atau TNI). Penyair yang karyawan itu bisa mengerahkan konco-konconya untuk membeli 1 atau 2 eksemplar buku lalu mengirimkan SMS dengan memilih puisi Fulan sebagai puisi terbaik.
Apabila dalam satu instansi saja, si Fulan bisa mendapatkan 300 orang pendukung, sudah lebih dari lumayan suara terkumpulkan, yakni 600 suara. Belum lagi, teman dari keluarganya yang kebetulan juga karyawan di instansi lain. Dan, akan lebih menguntungkan jika penyair Fulan bekerja di suatu instansi yang garis komandonya kuat. Ia cukup ''memerintahkan'' juniornya dan ''merayu'' seniornya untuk membeli buku dan mengirim SMS dukungan ke panitia!
Maka, penetapan ASPK memang bukan diukur sebagai prestasi. Tetapi, sekali lagi, cumalah permainan --seperti juga permainan dalam Akademi Fantasi Indonesia (AFI) di Indosiar dulu.
Kecuali kelalaian panitia, kalau saya tidak salah, antara perolehan suara untuk Inggit Putria Marga dan Dahta Gautama (juga Jimmy Maruli Alfian, ketiganya dari Lampung), mestinya Dahta berada di atas Inggit. Selebihnya, untuk apa kita sikapi secara serius final Anugerah Pena Kencana? Ya, anggaplah ini sebuah permainan, maka gak usah serius amat! Lalu lupakan, tapi tetap berkarya dan mengharap-harap pada ASPK jilid 2 nanti karya kita masuk nominie pemenang dan dibukukan. Syukur kalau kemudian karya kita dipilih pembaca sebagai karya terbaik dan memeroleh hadiah Rp 50 juta. Wah, bisa bikin rumah baru atau naik kuda nipon. (*)
Lampung, 2 Oktober 2008; 00.42
Minggu, 12 Oktober 2008
Lomba Puisi Sumpah Pemuda dan Rembug Budaya Metropoli 2008
Lomba penulisan puisi dan esai pemuda itu dalam rangka peringatan 80 Tahun Sumpah pemuda. Lomba khusus pelajar dan mahasiswa itu (naskah dilampiri fotokopi kartu pelajar atau kartu mahasiswa) sudah dimulai awal September lalu. Karya harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan. Untuk cipta puisi, naskah rangkap tiga dengan format bebas. Sedangkan untuk naskah esai, maks. 5.000 karakter, huruf times new roman 12 dengan spasi 1/5, dikirim rangkap tiga. Naskah akan dinilai juri Sapardi Djoko Damono dan Budi Darma. Juara I-III puisi mendapatkan hadiah Rp 1,5 juta, Rp 1 juta, dan Rp 750 ribu. Sedangkan juara I-III esai mendapatkan hadiah Rp 2,5 juta, Rp 2 juta, dan Rp 1,5 juta.
INTI juga mengadakan lomba futsal untuk pemuda. Lomba akan dilangsungkan 19 Oktober 2008 di Gedung Serbaguna KEP Pantai Ria Baru Kenjeran, Surabaya. Hadiah yang disediakan total Rp 6,5 juta. Info lebih lanjut hubungi panitia di 08175283993. (*/ari)
Sedangkan Rembug Budaya Metropoli 2008
Yayasan Metropoli Indonesia (YMID) menggelar ''Rembug Budaya Metropoli 2008'' di Dusun Tanah Lengis, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Karangasem, Bali, 18-21 Oktober. Rembug budaya akan dibuka bupati Karangasem pada 18 Oktober pukul 09.00. Ada pentas seni spiritual ''Panedeng Masa Kartika'' dari Saraswati Mahapradnya Saren; launching Majalah Wali; dan pentas Tari Janger Anak-anak dari Linggasana, Bebandem. Juga ada Pentas Gong Kebyar Anak-anak Dusun Umanyar, Ababi; drama tradisional Arja Men Brayut; lomba melukis dan Nyurat Aksara Bali; serta sarasehan budaya dengan pembicara pelukis Made Budhiana.
Pada hari kedua (19/10) diadakan lomba Gong Kebyar Anak-anak (6 grup), kampanye sampah plastik dan lingkungan, dan pemutaran film Bali Tempoe Doeloe. Pada hari ketiga (20/10) diselenggarakan lomba Tari Margepati dan Puspawresti, atraksi Tabuh Gender Anak-anak (Banjar Abianjero, Gunaksa, Umanyar), dan pentas Gambuh Anak-anak Saraswati Mahapradnya dengan lakon Calonarang. Sedangkan penutupan (20/10) akan diramaikan atraksi Yoga Asana Banjar Tanah Lengis, potong tumpeng ulang tahun YMID, dan pengumuman lomba.
Untuk informasi hubungi telp./fax. (0363) 22600 atau 081337143228, 081338084585. Email: director@metropolifoundation.org (Ni Made Sudani), myjengki@yahoo.com (Wayan Sunarta). (*/ari)
Sabtu, 13 September 2008
Cincin Kawin

saya begitu tertarik dan terkesan dengan gaya penulisan dari danarto. banyak yang berkata danarto adalah seorang penulis yang bermahzab "realisme magis". selamat menikmati cerpen ini.
Cerpen Danarto
Ketika ibu mendapatkan cincin kawinnya berada di dalam perut ikan yang sedang dimakannya, seketika ibu terkulai di meja makan, pingsan. Lalu koma sekitar satu minggu, kemudian ibu meninggal dunia. Sejak saat itu sejarah hidup keluarga kami diputar ulang. Seperti digelar di kamar keluarga, juga di pekarangan belakang rumah, hari demi hari diperlihatkan malaikat betapa cara kerja langit tak mempunyai patokan. Tak dapat ditebak. Tak terduga. Dalam mengarungi pemandangan yang terbentang di hadapan, kami tak tahu benar apakah itu pemandangan alam atau lukisan pemandangan alam di atas kanvas.
Kami juga sering turun dari kendaraan umum lalu beramai-ramai menambal aspal jalan yang mengelupas. Atau mendorong bus kami yang terjerembab banjir. Pemandangan indah, pemandangan suram, semua disajikan kepada kami.
Kami harus jujur, kami sekeluarga bukan kumpulan orang-orang baik tapi kami mematuhi rambu-rambu lalu-lintas. Hidup kami baik-baik saja sampai gempa yang berkekuatan dahsyat itu jatuh dari angkasa. Seluruh bangunan porak-poranda sampai sekecil-kecilnya rata dengan tanah. Nama, watak, kelakuan, pikiran, emosi, keberuntungan, dan nasib jelek, berputar-putar di dalam kubangan rajah tangan yang sudah dicetak di dalam K.T.P. yang tersimpan dalam segel laminasi dengan warna emas.
Jika kami bongkar, apa satpam tidak marah? Jika tidak kami bongkar, kami megap-megap. Tapi itulah harga mati dari rantai yang sudah telanjur bergandengan.
Hari itu hari yang mendidih. Walau hujan sehari-harinya, Desember yang hitam-pekat oleh bara yang menganga telah membayangi hidup kami sekeluarga setiap detiknya. Hari belum tinggi benar ketika ayah diseret ke tepi Sungai Brantas bersama puluhan orang --laki-laki dan perempuan-- yang duduk dengan mata tertutup dan tangan terikat ke belakang. Mereka basah-kuyup menggigil kedinginan oleh hujan dan kepanasan oleh hantu yang mengintip dari balik kancing baju mereka. Persis gundukan tanah yang tumbuh berderet-deret menghiasi sungai, mereka gundukan-gundukan yang tak dikenal. Gundukan semak belukar yang setiap saat dibabat supaya kelihatan rapi.
Ketika itu mata saya mengintip dari balik semak dalam hujan lebat yang tak mau tahu. Mata yang berumur sekitar dua puluh delapan tahun. Mata yang menatap tajam di antara tetesan hujan deras itu. Saya menyaksikan satu per satu dari leher orang-orang yang duduk termangu-mangu setelah disambar kilatan putih menyemburkan cairan merah dengan deras ke udara. Lalu tubuh-tubuh yang masih duduk tak berkepala itu didorong terjungkal ke sungai. Tubuh-tubuh itu tenggelam lalu tersembul kembali. Dalam sekejap mayat-mayat yang mengapung-apung itu memenuhi seluruh permukaan Sungai Brantas.
Rasanya hujan bertambah deras. Para petugas yang telah melaksanakan perintah itu, dalam keadaan basah-kuyup berlarian dengan pedang yang telanjang berkilatan oleh cahaya petir, menuju sejumlah truk yang telah kosong, lalu tancap gas meninggalkan kawasan itu. Dengan menjerit-jerit memanggili ayah, saya yang menggigil dalam hujan penuh geledek menyambar-nyambar, berlari menyusuri tepi sungai mengikuti mayat-mayat yang mengapung dibawa deras air.
Lalu saya terjun ke sungai berusaha keras mencari jenazah ayah. Saya menyembul dan menyelam di antara jenasah-jenasah itu, mencoba mengingat kembali baju apa yang dipakai ayah. Rasanya seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Hujan yang sangat deras menyebabkan permukaan air sungai penuh uap. Saya megap-megap. Saya berenang menepi setelah usaha saya sia-sia.
Mayat-mayat embun, taruhlah di nampan, jadi hidangan suci dari bau tangan yang gatal. Menyayat-nyayat dada, menyayat-nyayat air liur yang dijilati petir. Mayat-mayat yang menyembunyikan nama, watak, kelakuan, pekerjaan, emosi, elan vital. Mayat-mayat, puluhan, ratusan ribu, carilah dalam map dari para pencari data. Para pencari data yang berdatangan dari seantero dunia.
Memanggili ayah, memanggili nama dari halaman yang hilang. Mayat-mayat yang begitu mengerti mengantarkan kepala-kepala yang timbul tenggelam dalam air. Saya tidak bisa mengerti. Saya tidak bisa mengerti.
Yang mana tubuh ayah? Yang mana jenazah ayah? Saya mengikuti terus tumpukan mayat-mayat itu yang terus diseret sungai sampai menuju entah. Saya berlari terus, saya berlari terus, saya berlari terus . . .
Hari-hari yang sangat berat bermunculan. Hari-hari yang sangat berat yang harus kami panggul. Saya dikeluarkan dari pekerjaan saya sebagai pemasar barang-barang kebutuhan dapur karena dianggap tidak bersih lingkungan. Begitu juga kakak perempuan saya, Retno, guru SMP. Masih untung, adik saya, Ning, yang bekerja di sebuah usaha kerajinan rakyat, alhamdulillah, masih boleh bekerja. Mungkin karena Ning masih kecil. Sementara itu uang tabungan ibu semakin menipis.
Waktu itu kabar merebak, ikan-ikan yang harganya masih murah sebagai lauk, mulai ditinggalkan karena di dalam tubuh ikan-ikan itu biasa ditemukan potongan jari, bola mata, usus, maupun barang-barang yang menempel di tubuh-tubuh mayat yang memenuhi Sungai Brantas.
Kami masih bertahan makan ikan karena harganya semakin murah, sampai ibu menemukan cincin kawinnya yang dipakai di jari ayah. Hari-hari semakin bertambah berat bagi kami bertiga yang semakin lemah menjalaninya, ketika kami merawat ibu yang koma satu minggu lamanya dengan makanan seadanya yang sangat tidak pantas dan menguburkannya pada hari ke delapan.
Kami bertiga menangis dengan airmata yang menusuk-nusuk hulu hati, mengantarkan jenazah ibu yang diusung oleh para tetangga yang kasihan melihat penderitaan kami. Di gundukan kuburan itu, Ning menangis sejadi-jadinya sambil mencakar-cakar tanah gundukan.
Beberapa bulan kemudian merupakan hari-hari teror dan horor menghantui kami karena di waktu dini hari kami sering terbangun dari tidur terkaget-kaget oleh gedoran orang-orang. Mereka merangsek masuk mencari buron. Mengoprak-oprak kamar tidur kami, memeriksai kolong tempat tidur, dipan, lemari pakaian, dapur, plafon, maupun kebun belakang. Sering Ning terbangun dari tidur menjerit-jerit memanggil ayah, memanggili ibu. Baru reda setelah dipeluk Retno. Sungguh saya tidak bisa mengerti mengapa kami kecebur dalam kubangan begini rupa tetapi kami harus bertahan atau kami hancur berantakan. Saya bekerja serabutan. Apa saja saya kerjakan untuk bisa bertahan hidup. Termasuk jadi tukang sapu pasar.
Hari-hari yang mengerikan itu sering mendorong nyawa kami sampai di tenggorokan. Nyawa yang digondeli raga sekuat-kuatnya. Supaya tidak terlepas. Supaya tetap betah menghuni di dalam tubuh kami dalam keadaan sengeri apa pun. Duh, raga, gondelilah nyawa.
Rasanya tubuh kami tinggal kulit pembalut tulang. Kecantikan Retno yang mewarisi kecantikan ibu, lenyap. Retno tinggal kering kerontang, tanpa seyum, tanpa harapan. Begitu juga Ning yang tampak lebih cantik dari kakaknya, persis anak gelandangan yang memakan apa saja supaya perut tidak lapar. Segala puji bagi Allah Yang Maha Suci, kami masih memiliki rumah tempat kami berlindung dan tempat kami menangis sepuas-puasnya.
Diam-diam saya sering mengunjungi kuburan ibu. Saya tumpahkan segala unek-unek sambil berlelehan air mata. Juga saya mendoakan ibu semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengaruniai ibu kebahagiaan di akhirat. Kadang saya merasa ibu hadir di samping saya yang membuat saya menangis sejadi-jadinya.
Saya juga sering menapak-tilasi tempat ayah terduduk di tepi sungai bersama puluhan orang sebelum dieksekusi. Saya meraba-raba pasir yang mungkin keringat dari kaki ayah masih tersisa. Saya memeluk dan menangisinya sambil memohon Allah mengampuni dosa-dosanya dan mengaruniai ayah kenyamanan di akhirat.
Ayah adalah kepala SMP. Semua kegiatan ayah berkisar antara rumah dan sekolah. Hampir tak pergi ke mana-mana. Jika sekolah piknik, ayah tak pernah ikut. Ia menugaskan guru yang lebih muda. Ayah cukup berbahagia mendampingi ibu yang sibuk dengan usaha kateringnya. Ayah tak tertarik politik. Beliau murni seorang pendidik. Setiap kali saya terbangun tengah malam atau dini hari, ayah dan ibu tampak sedang khusyuk beribadah yang membuat saya malu hati karena siapa tahu sedikit banyak sapuan ibadahnya juga untuk keselamatan hidup saya, seorang anak yang barangkali saja tidak memiliki dimensi spiritual, kurang bersyukur, tak menyadari dilahirkan oleh sepasang orang tua yang selalu menginjakkan kakinya di halaman surga, di mana tak semua orang mampu pergi ke sana.
Sampai malam malapetaka itu mengetuk pintu rumah kami dan membawa ayah pergi. Untuk sesaat, saya, ibu, Retno, dan Ning tertegun, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang yang menggelandang ayah begitu garang, juga tak bersedia memberi alasan.
Beberapa tetangga yang ikut jadi korban berkumpul di rumah kami, saling bertanya boleh jadi di antara kami ada yang jauh lebih mengerti akan situasi yang terjadi.
Di rumah kami inilah semuanya bertangis-tangisan meluapkan kesedihan masing-masing, seperti gaung yang tak henti-hentinya, tak bisa dimengerti, tak bisa dimengerti, tak bisa dimengerti . . .
Yang saya takutkan setelah meninggalnya ibu, Retno dan Ning tergoncang jiwanya sehingga menjadi tidak waras. Saya ikuti terus perkembangan jiwa keduanya. Saya cukup lega, keduanya cukup sehat, hanya saja kesehatan Retno dari hari ke hari terus memburuk.
''Bertahanlah, Retno,'' bisik saya di telinga Retno yang membujur kaku dan panas. ''Jangan kecewakan ayah dan ibu. Jangan bikin ayah dan ibu menangis di dalam kuburnya. Kamu harus bangun dan bekerja. Kita bertiga harus bekerja supaya ayah dan ibu bangga.''
Ning memeluk erat-erat Retno sambil menangis keras-keras.
Setelah sakit beberapa lamanya, Retno muntah darah. Karena ketiadaan obat dan makanan yang baik, akhirnya Retno meninggal.
Retno saya kuburkan di samping kuburan ibu. Setiap hari saya kunjungi kuburannya yang menyadarkan saya bahwa saya telah gagal menyelamatkan keluarga kecil ini. Apalagi Ning pergi meninggalkan saya entah ke mana.***
Tangerang, 20 Januari 2008
Senin, 09 Juni 2008
Pertemuan dengan penari kecil di stasiun kereta tua
Pertemuan dengan penari kecil di stasiun kereta tua. Saya terpaksa menoleh memperhatikan penari itu. Seakan di bawa dalam hal magis. Terkelebat bayangan Soe yang terjaga. Hari ini! Saya merasa di siksa. Saya di tarik-tarik oleh hawa semilir bau hujan di akhir mei. Mata ini lelah dalam kungkungan kalimat atau bahkan muak.
Tepat pukul 17.00 arloji di pergelangan tangan. Terlintas jelas seakan sore ini tidak bisa sedikitpun bisa berlari dari kelebatan Soe. Matanya yang begitu sayu. Kunang-kunang hanya berkelip. Tapi matanya adalah bius, lebih dari opium yang memabukkan.
Penari kecil yang menari begitu megah di antara buni rintihan rel kereta yang mendecit. “Biar” Tiba-tiba tersentak. Penumpang lain pun merasa terganggu dan denagn lemah terpaksa harus megatakan kata maaf atas ketidak nyamanan yang saya buat. Tampak seorang ibu dengan bayi di gendongannya. “Harus mengalah”dalam hati. Ibu itu adalah penumpang yag naik dari setasiun dengan penari kecil. “Bu, silakan,” sambil berdiri. “Makasih nak,” ucapnya.
Kamu sedang mengerjakan apa Soe? Langsung saja HP dalam saku celana kiri sudah berpindah ke tangan kiri ini. Langsungn saja tangan ini seolah sudah tahu harus bagaimana. Dengan lancar tulisan muncul. Dan berbunyi. “lg ngaps neeh ”. Saya langsung mengirim menuju nomornya.
Senin, 14 April 2008
Semeter Dari Meja Tuan
* * *
“Dua tahun lagi aku akan kembali.”
Begitulah ungkapan Hudan ketika ia meninggalkan tempat ia sendiri tidak tahu kapan bangunan ini di bangun. Pondasinya seperti tak mudah tergerus jaman. Gaya arsitektur dari belanda nampak menonjol di setiap jengkal bangunan tersebut. Tak terbayangkan jika bangunan megah yang akan ia tinggalkan mungkin hasil keringat budak-budak belanda(orang Indonesia).
Banyak sudah hasil selama ia di sini. Dari istri yang sudah dua, enam anak pun masih kurang. Sebuah vila di perukitan dengan furniture mahal sebagai hiasan cukup untuk menghiasi akhir pekan Hudan. Istri mudanya sepertinya baru dua tahun lalu muncul di TV. Berita terbaru setengah tahun lalu melahirkan anak dan ia belikan perumahan elit di daerah bukit golf ternama di Surabaya.
Di bangunan tua itu, tuan Hudan hampir lebih sepuluh tahun di pilih oleh direksi untuk memimpin perusahan jawatan pemerintah. Kedudukan itu terasa begitu cepat dan mudah ia mendudukinya. Cepat karena dalam hitungan lima belas tahun ia sudah jadi pemimpin. Dikatakan mudah karena banyak yang membantu termasuk mertuanya yang menjadi salah satu direksi perusahaan jawatan ini.
Namun rekan-rekan senior hanya mencibir dan tersenyum kecut dengan pengangkatan Hudan. Mereka diam, dan bergunjing di belakang direksi kalau tidak, ya… dilakukan ketika makan siang.
* * *
Perubahan terjadi tak semudah membalik telapak tangan tapi perjuang yang berat harus ia lalui. Dia masih ingat akan setiap pagi punggungnya selalu penuh dengan gallon air duapuluh liter-an hanya untuk mandi. Setelah pulang sekolahpun kebiiasan paginya ia lalui hampir tanpa ad perbedaan. Yang mebedakan hanya panas membakar kulit si Hudan yang mengkilap.
Hudan kecil selalu menjadi bahan lempran atau samsak teman teman-nya yang badannya lebih besar. Namun siksaan teman-temannya hanya sepintas lalu ia menganggapnya tubuhnya terlalu sering disiksa hanya karena adiknya menangs ataupun ia terpaksa tertidur akibat kecapekan.
SMP dan SMA pun tidak ada perubahan yang signifikan dengan kehidupan Hudan. Yang membedakan Hudan remaja lebih berprestasi dan kelihatn kekar di balik tubuhnya yang mengkilap.
Ancaman dan teror teman kecilnya sudah berkurang malahan hampir tak pernah ia temui. Hanya sedikit pergesekan yang lumrah sesama remaja. Hudan lulus tidak mengecewakan rangking empat di sekolahanya. Hal itu membuat ia berkesempatan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi negeri secara gratis hadiah dari sekolahnya. Ujian pun tidak ia jalani dengan mulus orang tuanya seperti tidak mengingnkan Hudan berkuliah. Tapi dengan sedidkit pemberontakan dan rayuan dari kepala sekolah akhirnya ayah hudan mengizinkan Hudan mengikuti ujian.
Dari sinilah Hudan memulai perubahannya. Di terima menjadi mahasiswa lalu ia mengkuti sebuah gerakan pembaruan kampus(itu yang ia katakan). Pernah ia terpotret wartawan dan masuk berita Koran sekali ketika ia berdemo dengan teman aktifis di kampusnya. Langsung ia mengkopi Koran tersebut lalu ia bawa pulang ke desanya dan disebar dari tetangga pak RT, RW, lurah carik hingga camt ia beri kopian Koran yang memuat gambarnya berdemo. Tak luput ia beri ke Susi bunga desa pujaannya.
Seakan gayung bersambut Koran itu pula yang menggiring kepada mertuanya. Mertuanya yang saat hudan berdemo sebagai pimpinan jawatan itu merasa risih. Denag banyak cara Hudan akan dia hentikan kalau perlu malah-malah akn di bunuh sekalian katanya.
Perjuangan calon mertua hudan tak menghasilkan apa-apa . pada akhirnya tanpa piker panjang untuk menghentiakn demo itu dia mencari pemimpin demonya, yaitu hudan. Dengan sangat terpaksa pimpinan jawatan itu menawarkan anaknya yang cantik mahasiswa satu fakultas hudan untuk dinikahkan dengan hudan dengan jaminan kedudukan di perusahaan jawatan yang ia pimpin.
Seperti di sambar petir ke idealis-an Hudan hangus begitu saja. Hanya dalam hitungan menit ia mengiyakan. Belum ada sebulan dari negosiasi terkabar Hudan sudah menikahi anak Pimpinan jawatan itu.
Yang jelas Hudan merasa bangga dan mulai membenci masa lalunya. Seakan ia melewati kentut yang tertiup angin dan melupakan Susi gadis desa pujaannya. Ayah dan keluarganya adalah masa lalu yang lewat da hanya menjadi bagian dari sejarah Hudan menantu seorang mantan pemimpin perusahaan jawatan yang telah masuk ke dalam jajaran direksi. Dan hudan menjadi salah satu pegawai perusahaan jawatan itu.
* * *
Hari pertama lepas dari masa suramnya setelah diangkat menantu seorang pemimpin perusahaan jawatan plus bonus sebagai pegawai jawatan pimpinan mertuanya. Tak banyak rekan sekerjany yang tahu kalau Hudan adalah anak mantu sang bos. Soalnya muncul pergunjingan jika pimpinan mereka telah menjual anaknya demi kepentingan diri sendiri. Rekan kerja Hudan banyak yang kaget mengetahui yang menikahi anak sang pemimpin adalah Hudan yang pemimpin pendemo dari kalangan mahasiswa yang mengatas namakan rakyat kecil. Banyak pegawai berfikir gerakan mahasiwa ini sukses akan membawa perubahan yang besar dalam tubuh perusahaan jawatan ini. Ada pula yang berdoa semoga meletus gerakan 65 kedua agar hidup lebih baik. Tapi fakta berbicara, Hudan menjadi menantu pimpinan serta menghianati perjuangan rekan-rekannya dan kecewa para direksi.
Akumulasi kekecewaan semakin menumpuk ketika para seniaor di tempat kerjanya tergusur dengan mudah seakan tak pernah ada sebelumnya. Hudan yang mantan aktifis itu seperti tidak peduli, ia melenggang begitu saja dan berlalu. Prilaku kesewenang-wenangan Hudan mulai muncul ketika memimpin rapat tingkat pimpinan bagian. Progam yang ditawarkan hudan tidak lebih baik dari yang lain
* * *
Kehidupan barunya boleh jadi normal-normal saja tak ada yang istimewa. Yang membuat lain dari yang kebiasaannya ia telah jadi orang kaya. Air tinggal putar. Tidur di kasur yang empuk bukan lagi seperti dulu harus berjalan jauh demi dua puluh lima liter air dan hilanglah bayangan bale yang penuh ketakutan. Ini ajaib menurutnya. Sangat spesial tak pernah ia bayangkan hidup ini.
Pernah sekali ia pulang kerumahnya di desa dia sudah mendapati Susi menikah dengan Kartono teman sepermainannya. Yang paling diingat dari kartono adalah pukulan membabi buta pada tubuh gilapnya. Tapi Hudan tidak mau bertemu apalagi menatapnya. Hudan meludah tept dihadapan Kartono melaui jendela mobilnya.
Di desa, Hudan pertama kali tidak menemui adik ataupun orang tuanya. Tapi malah kepala sekolahnya ketika ia SMA yang di temui dengan memberi oleh-oleh yang cukup banyak untuk ukuran desa. Di rumahnya sendiri Hudan hanya memberi uang saku adik-adiknya lalu pergi pulangt kekota dengan alasan di kota pekerjaan masih menumpuk.
* * *
Malam hari,dalam liburan panjangnya Hudan selalu duduk di atas meja tebal dari kayu jati berumur ratusan tahun yang katanya hadiah pertama yang diberikan koleganya dimasa awal dia menduduki jabatan pimpinan jawatan itu. Si Abdi selalu setia menemani denga hanya memberikan segelas besar kopi buatan istri abdi.
Sebenarnya Hudan kepada para pembantunya sangat baik malah bisa dikatakan kelewat. Atau itu merupakan sebagian dari hati kecil Hudan. Ataukah hanya apresiasi karena telah menemani hudan “bersembunyi”. Tapi Hudan tetaplah Hudan yang selalu serampang dalam menentukan sesuatu. Serasa kematian sudah mendekat ketika tak sadar ia di temukan Abdi tergeletak di bawah meja. Abdi pun menemukan botol-botol berserakan. Tidak hanya sampai itu saja malahan Hudan pernah sampai mengucurkan darah ketika ia tak sengaja kena pecahan kaca bear yang ia minum di malam hari. Hal itu pun terus terjadi dan sudah tak terhitung berapa kali ia hampir mampus karena kelakuannya sendiri.
Orang-orang kampung dekat pengsingannya hanya diam sesekali ada yang memberanikan bertanya pada Abdi. “Banyak sekali pecahan kaca dari tuanmu pa dia buat pabrik botol ya.” Dengan wajah desa dan melindungi tuannya abdi hanya bilang kucing yang menjatuhkan botol bear koleksi. Jawaban itu sebenarnya bukan murni dari si Abdi tapi hal itu seperti yang di kehendaki tuannya. Tempat pengsingan ini selau tertutup untuk masyarakat biasa. Namun Hudan selalu tersenyum manis ketika hrus berpapasan dengan warga desa setempat. Hanya pak lurah yang pernah masuk ke dalam rumah itu.
* * *
Si Abdi hanya duduk diam di pekarangan tuannya. Di terlalu takut dengan ancaman nyonya besarnya yang tadi malam datang dengan seorang teman. Katanya sih hanya menemui tuan mau diajak bicara masalah tuan muda. Kedatangan nyonya sangat mendadak. Saat si abdi baru saja datang istrinya membawakan kopi untuknya dan tuan Hudan.
Tanpa di sadari ketika Abdi meninggalkan ruangan tuanya, langkahnya terhenti oleh letusan ynag sungguh mengagetkan. Tak disangka di antara bunyi letusan pistol tiba-tiba nyonya melihat abdi yang dengan sigap langsung menuju pusat letusan dengan membawa sabitnya. Ternyata yang memegang pisto adalah seorang dekat nyonya yang mengacungkan pistolnya pada tuan. Tanpa ba, bi, bu langsung nyonya menyumpali telinga dengan ancaman-ancaman yang membuat miris dan ketakutan berlebih. Tuan terbunuh oleh istri pertamanya. Dan itulah fakta yang harus di tutupi dengan sedikit ancaman yang meneror bisa tertutupi.
Tuan tergeletak di meja. Si Abdi mulai membersihkan darah di antara meja. Berlari pun tak bisa. Di melakukan pekerjaan sebagai pembantu. Yang dilakukan cuma berdiri semeter dari meja. Sambil melihat kopi buatan istrinya yang kelihatan masih hangat.
November 2007
di muat di Gema
Selasa, 01 April 2008
KEBUDAYAAN HILANG, TANGGUNG JAWAB SIAPA?
Pecahnya G 30 S PKI membuyarkan seluruh persendian dan aspek-asapek sosio-kulktural di masayarakt Indonesia secara keseluruhan, baik kota maupun desa. Di pelosok-pelosok pedesaan hal serupa berlaku tanpa ampun. Sampai-sampai terkabar hilnagnya orang-orang yang tidak jelas dimana dan kemana.
Tidak cukup dengan hilangnya orang (nyawa) namun aspek yang menunjukkan ke khasan suatu daereah pun ikut juga menghilang. Hal ini disebabkan oleh sebuah lembaga yang menjadi organisasi sayap dari partai besar(PKI) masa ORLA yaitu Lembaga Kebudayaan Rakyat (selanjutnya disebut LEKRA). Dalam praktek kebudayaan yang di usung oleh Lekra adalah kebudayaan yang mengakar di kehidupan rakyat, salah satunya adalah REOG Ponorogo.
REOG digunakan Lekra sebagai alat kampanye untuk meraih pemilih sebanyak-banyaknya. Setelah pecahnya G 30 S reog di bumi hanguskan dari peredaran. Banyak dari pengurus kelompok kesenian tradisi ini mulai meninggalkan. Bahkan pernah terdengar mereka semua di cap sebagai PKI dan halal hukumnya untuk dibinasakan. Sampai-sampai banyak REOG yang dibakar, dikubur dan jika beruntung di antara para seniaman REOG melarikan diri baik di daerah lain di Indonesia tercinta maupun ke Mancanegara(seperti Malaysia). Dari sinilah yang nanti akan menimbulkan polemik baik dalam maupun luar negeri.
span="" class="fullpost"> Reog yang jelas-jelas kesenian yang mengakar di daerah Ponorogo seakan luruh dan telah menjadi kesenian suatu daerah dii Malaysia(tepatnya penulis lupa). Hal ini merupakan pukulan yang sangat telak yang pernah terjadi bagi warga pemiilk sah dari kebudayaan Reog.
Jika di telusuri lebih dalam, hal ini tidak lepas dari kongres dalam menentukan kebudayaan Indonesia itu seperti apa. Ki Hajar Dewantoro menyatakan kebudayaan Indonesia adalah puncak-puncak dari kebudayaan daerah. Hal ini tidak berlaku untuk REOG Ponorogo yang Notabene merupakan identik dengan Lekra. Alasan ini lah yang menyebabkan Reog tidak bisa menjadi puncak kebudayaan daerah. Celah inilah kelak di gunakan oleh Malaysia mengakusisi paksa, di tambah banyknya warga keturunan Ponorogo (pelarian) banyak berdomisili di negeri yang mengaku serumpun itu.
Warga keturunan ini sanggat rindu akan kebudayaan yang ia banggakan, hingga pada akhirnya memtusakan untuk membuat pementasan REOG di Malaysia. Sebenarnya pengembalian citra Reog telah dilakukan pada masa ORBA. Namun sama halnya PKI masa ORLA di Masa ORBA semua reog yang ada di Ponorogo berwarna Kuning(sebut saja di Golkar-kan) sebagai ganti dari pengembalian citra dan pembersihan nama para petinggi REOG.
Ironis memang sebuah kebudayaan yang tak ternilai harganya harus selalu menjadi bulan-bulanan partai-partai demi kekuasaan. Semakin di perparah dengan keacuhan para pemuda dalam hal pelestarian (yang mengatakan Kuna) menjadi alasan klasik. Semakin diperparah dengan perampasan kebudayaan secara paksa yang dilakukan negeri tetangga Malaysia menjadikan pemilik sah warga asli maupun keturunan Ponorogo mengalami kegelisahan memeuncak.
Peristiwa yang memalukan kedaulatan bangsa ini seharusnya tidak usah mencari kambing hitam siapa penyebabnya. Namun, menurut hemat saya bisa di jadikan sebuah pelajaran. Dan jika boleh mengutip tulisan Prof. Budi Darma hal ini bisa di sebut musibah peringatan mengenai pentingnya menjaga kebudayaan yang menjadi Tanggung Jawab umat manusia.
Tanpa mengecilkan perannya dalam masyarakat, dimanakah posisi Mahasiswa(pemuda) sebagai pewaris sah dari kebudayaan Nusantara. Akhirnya sebagai pewaris sah kebudayaan penulis hanya bisa berucap “dengan menyebut nama Tuhanmu” semoga kita tidak mendapat Hukuman.
Wallahua ‘lam
Surabaya, 29 Februari 2008


.jpg)