SETELAH buku Anugerah Sastra Pena Kencana 2008 (cerpen dan puisi) dilepas di pasar, kedua buku itu langsung menuai kritik. Setumpuk kritik tersaji di milis-milis. Belum lagi pesan pendek yang beredar melalui handphone ke handphone. Intinya, kalau tidak mempertanyakan ya menghujat cara penjaringan dan penilaian --termasuk kepada dewan juri dan panitia yang karyanya masuk dalam buku.
Pemberian anugerah karya sastra di Tanah Air bukan kali ini saja yang panen kritik, tapi sudah berulang-ulang seiring bergulirnya anugerah. Contoh yang sangat dekat ialah KLA (Katulistiwa Literary Award), SEA Write Award, dan sebagainya.
Tradisi kritik memang sudah mendarah daging di negeri ini. Tetapi, ''tradisi'' tersebut muncul tersebab ''budaya'' kita juga yang kerap abai pada aturan-aturan yang telah disepakati. Atau longgar dan menyepelekan persyaratan yang sudah diteken; aji mumpung dan menganggap masyarakat dapat ''dipaksa'' untuk menyetujui setiap keputusan yang diambil.
Sampai kini KLA tak sepi oleh kritik. Misalnya, soal penjurian tingkat awal untuk ''memburu'' buku-buku sastra di toko buku (konon, prioritas TB Gramedia) yang ada di Jakarta. Mereka ''dimodali'' untuk membeli sejumlah buku, kemudian mengajukan judul buku yang dipilihnya untuk mengikuti penyaringan.
Sampai di sini, kelihatannya tak ada masalah. Pertanyaan pun lalu muncul: siapa (mereka) yang dipercaya penyelenggara untuk memburu buku sastra? Berapa ''modal'' yang diberikan kepada mereka dan dengan modal itu berapa buku yang harus dibeli dan dibaca. Apakah panitia mengaudit modal dan buku yang dibeli? Sikap ''saling percaya'' rasanya tidak tepat dilakukan di sini.
SEA Write Award yang ditaja Pusat Bahasa juga tak terelakkan menuai kritik. Bahkan acap sulit diterima akal, kenapa si Fulan mendapat SEA Write Award tahun ini dan mengapa si Bolan yang nyata-nyata buku-buku karyanya --secara kuantitas dan kualitas-- dapat dipertanggungjawabkan, justru tidak terpilih? Sebab itu, SEA Write Award lalu dianggap ''anugerah arisan'' karena memang yang sudah pernah mendapat tidak akan mendapat lagi. Seorang teman tatkala memeroleh anugerah itu, melalui pesan pendek, dengan gurau berujar: ''Kali ini giliran aku yang mendapat arisan.''
Itulah sedikit gambaran fenomena award-award di ranah sastra Tanah Air. Sebenarnya masih banyak, termasuk Ahmad Bakrie Award, Akademi Jakarta, dan seterusnya. Pemberian anugerah sama tipisnya dengan penetapan sastrawan yang (akan) diundang ke luar negeri: sama-sama berisiko dikritik dan sama-sama ''bermain''.
Ya! Bicara soal ''bermain'' memang kehidupan ini adalah permainan. Karena permainan, lakoni saja dengan penuh keriangan. Dengan kata lain, gak usah serius amat, bermain-main saja, santai. Meminjam moto konco-konco di KoBer (Komunitas Berkat Yakin): rock n roll hahaha.
Lalu, apakah karya sastra bukan lahir dari keseriusan? Soal ini, siapa pun setuju 100 persen. Antara karya sastra dan penilaian award acap tak dapat dicari titik temu dan titik tujunya. Lha wong sekelas Nobel saja tak bebas kritik, kok.
Aturan-aturan dalam penentuan suatu pilihan dibuat sangat ideal. Tetapi, seideal apa pun tetap punya celah untuk ''dimainkan'', lalu jadi ''ketetapan baru''. Undang-undang, AD-ART, dan apa pun namanya selagi yang buat manusia, ia punya ruang untuk dilanggar.
Demikian pula dengan Anugerah Sastra Pena Kencana (ASPK) 2008. Setahu saya dari milis-milis, puisi-puisi Joko Pinurbo -penyair yang juga salah seorang dewan juri ASPK-- melanggar deadline antara pemuatan di koran dan kesepakatan dalam penjurian (Maafkan kalau apa yang saya kemukakan ini salah).
Tulisan ini tak akan jauh memasuki masalah puisi-puisi Jokpin. Saya --dan barangkali banyak pembaca sastra-- hanya mempertanyakan kepatutan apa sehingga para juri juga berhak menilai karyanya? Pertanyaan ini kita sempitkan saja: pantaskah juri merangkap menjadi peserta, meskipun berdalih juri tersebut tak ikut menilai ketika karyanya diajukan; artinya juri-juri lain yang menilai, dan seterusnya.
Kelihatannya tak ada masalah. Namun, sesungguhnya di situlah masalahnya. Analoginya demikian: puisi Fulan (bukan juri) dinilai oleh seluruh juri, sedangkan puisi Bolan (kenetulan juga menjadi juri) dinilai juri lain (minus dirinya). Kenetralan dirinya --kalau mau dikatakan netral-- sekaligus berpihak. Betapa tidak, ketidakikutsertaan dalam menentukan karyanya sendiri, sesungguhnya ia sudah memberi nilai pada karyanya. Tinggal teman-teman jurinya yang lain yang memberi bobot atas karyanya. Adilkah itu, dan di mana keadilannya?
Lalu, kritik yang juga meruak adalah ihwal karya-karya dari panitia yang lolos dalam buku tersebut. Rupanya panitia juga tak hendak dipisahkan dirinya sebagai kreator. Karena itu, dia ''minta keadilan'' agar karyanya ikut dalam bursa pemilihan. Soal ini juga kelihatannya tidak bermasalah. Para panitia akan berdalih: sebagai sastrawan karya kami juga punya hak untuk dinilai, dan jangan dikaitkan statusnya sebagai kreator dan bagian dari penyelenggara. Jika dalih ini terus dipelihara, bisa sangat berbahaya. Bagaimanapun kedekatan emosional antara panitia, juri, dan sebagai kreator tidak bisa dianggap sepele.
Kritik lain, saya pernah dikirimi pesan pendek dari seorang sastrawan Riau. Ia meragukan keakuratan saat perekrutan karya-karya yang terpublikasi setahun berjalan itu dari bebagai koran di sejumlah kota di Tanah Air. Pasti ada yang luput. Ia ambil gampang saja. Satu koran akan menurunkan beberapa puisi dan satu cerpen setiap pekan. Dikalikan setahun, jadilah 48 kali terbit (tak termasuk hari libur yang mungkin bertetapan pada Minggu). Lalu dikalikan minimal 5 puisi atau 7 puisi. Jadi, untuk satu koran saja, setahun bisa menginventarisasi sedikitnya 240 puisi. Nah, berapa koran yang ditelisik panitia ASPK? Dan, apakah setiap pekan dari media-media yang ditetapkan panitia tersebut dijamin tidak akan luput dari penyaringan panitia?
Seorang penyair lain berkelakar, ASPK tak lebih hanyalah ''permaianan''. Ia sepakat dengan contoh-contoh seperti yang sudah dikemukakan di atas. Itu sebabnya, teman penyair itu --kebetulan karyanya masuk dalam 100 Puisi Pilihan ASPK 2008 mengaku tak tetarik mengikuti babak pilihan pembaca buku itu melalui SMS (short message system).
Dari awal saja sudah permainan, karena itu tak perlu serius-serius amat, teman penyair itu menegaskan. Sebab, kalau kita mau ikut dalam permainan itu, kudu punya modal.
Sampai di sini, kita berkalkulasi dengan modal. Harga buku karya ASPK 2008 Rp 50 ribu per eksemplar. Sekiranya memiliki modal Rp 30 juta, kita akan mengantongi minimal 600 suara. Kalau menang, masih untung Rp 20 juta. Sebab, pemenang anugerah ini mendapatkan Rp 50 juta. Lumayan kan? Namun, dengan perolehan suara yang cuma 600 itu belum apa-apa. Posisinya masih gambling. Karena itu, perlu siasat lainnya: mengontak saudara, teman, kolega, dan seterusnya agar bersedia memberi dukungan.
Mari berandai-andai. Penyair Fulan kebetulan seorang karyawan (lebih baik lagi karyawan yang memunyai jenjang komando semisal di kepolisian atau TNI). Penyair yang karyawan itu bisa mengerahkan konco-konconya untuk membeli 1 atau 2 eksemplar buku lalu mengirimkan SMS dengan memilih puisi Fulan sebagai puisi terbaik.
Apabila dalam satu instansi saja, si Fulan bisa mendapatkan 300 orang pendukung, sudah lebih dari lumayan suara terkumpulkan, yakni 600 suara. Belum lagi, teman dari keluarganya yang kebetulan juga karyawan di instansi lain. Dan, akan lebih menguntungkan jika penyair Fulan bekerja di suatu instansi yang garis komandonya kuat. Ia cukup ''memerintahkan'' juniornya dan ''merayu'' seniornya untuk membeli buku dan mengirim SMS dukungan ke panitia!
Maka, penetapan ASPK memang bukan diukur sebagai prestasi. Tetapi, sekali lagi, cumalah permainan --seperti juga permainan dalam Akademi Fantasi Indonesia (AFI) di Indosiar dulu.
Kecuali kelalaian panitia, kalau saya tidak salah, antara perolehan suara untuk Inggit Putria Marga dan Dahta Gautama (juga Jimmy Maruli Alfian, ketiganya dari Lampung), mestinya Dahta berada di atas Inggit. Selebihnya, untuk apa kita sikapi secara serius final Anugerah Pena Kencana? Ya, anggaplah ini sebuah permainan, maka gak usah serius amat! Lalu lupakan, tapi tetap berkarya dan mengharap-harap pada ASPK jilid 2 nanti karya kita masuk nominie pemenang dan dibukukan. Syukur kalau kemudian karya kita dipilih pembaca sebagai karya terbaik dan memeroleh hadiah Rp 50 juta. Wah, bisa bikin rumah baru atau naik kuda nipon. (*)
Lampung, 2 Oktober 2008; 00.42
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


.jpg)

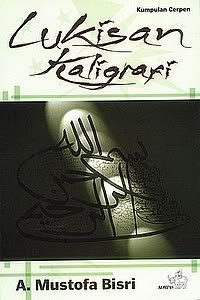

Tidak ada komentar:
Posting Komentar